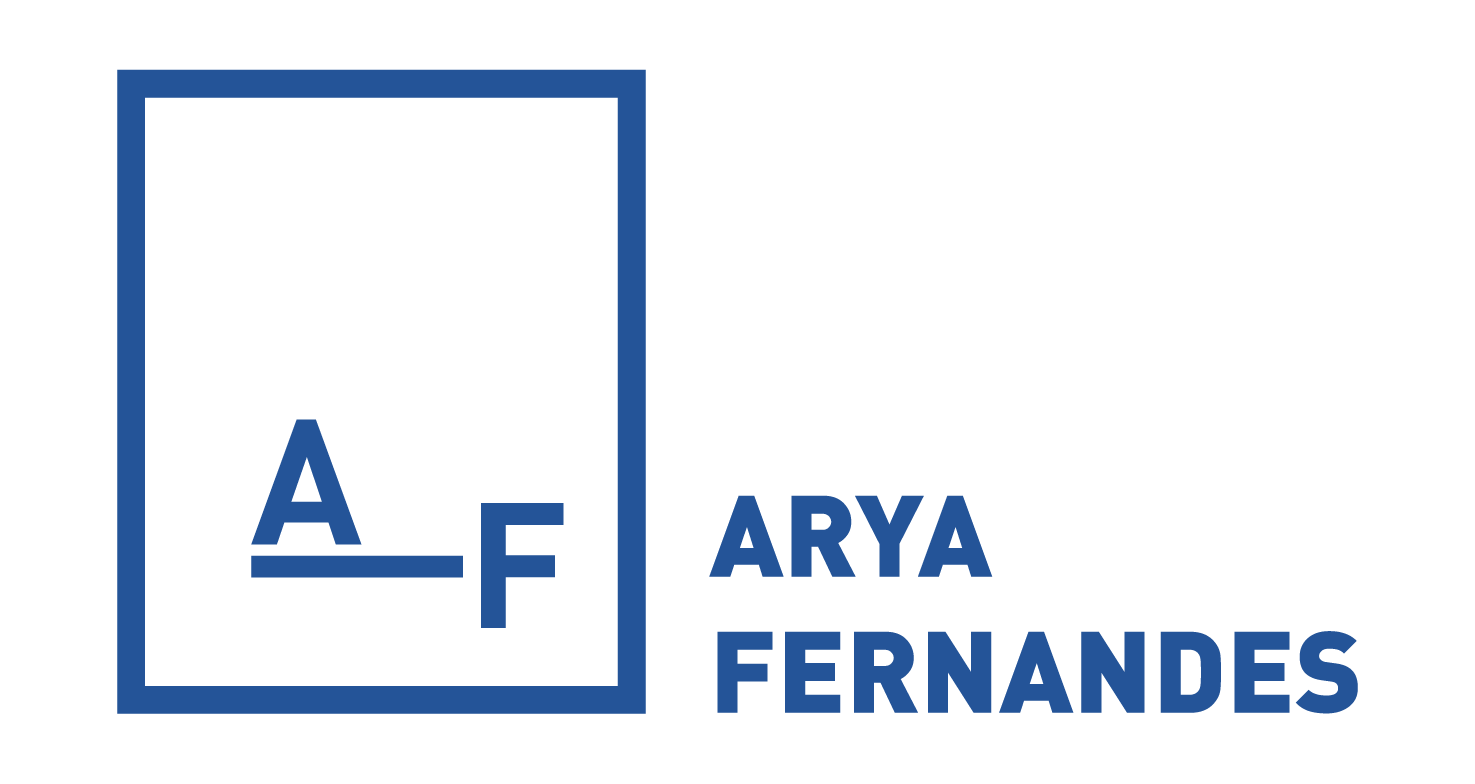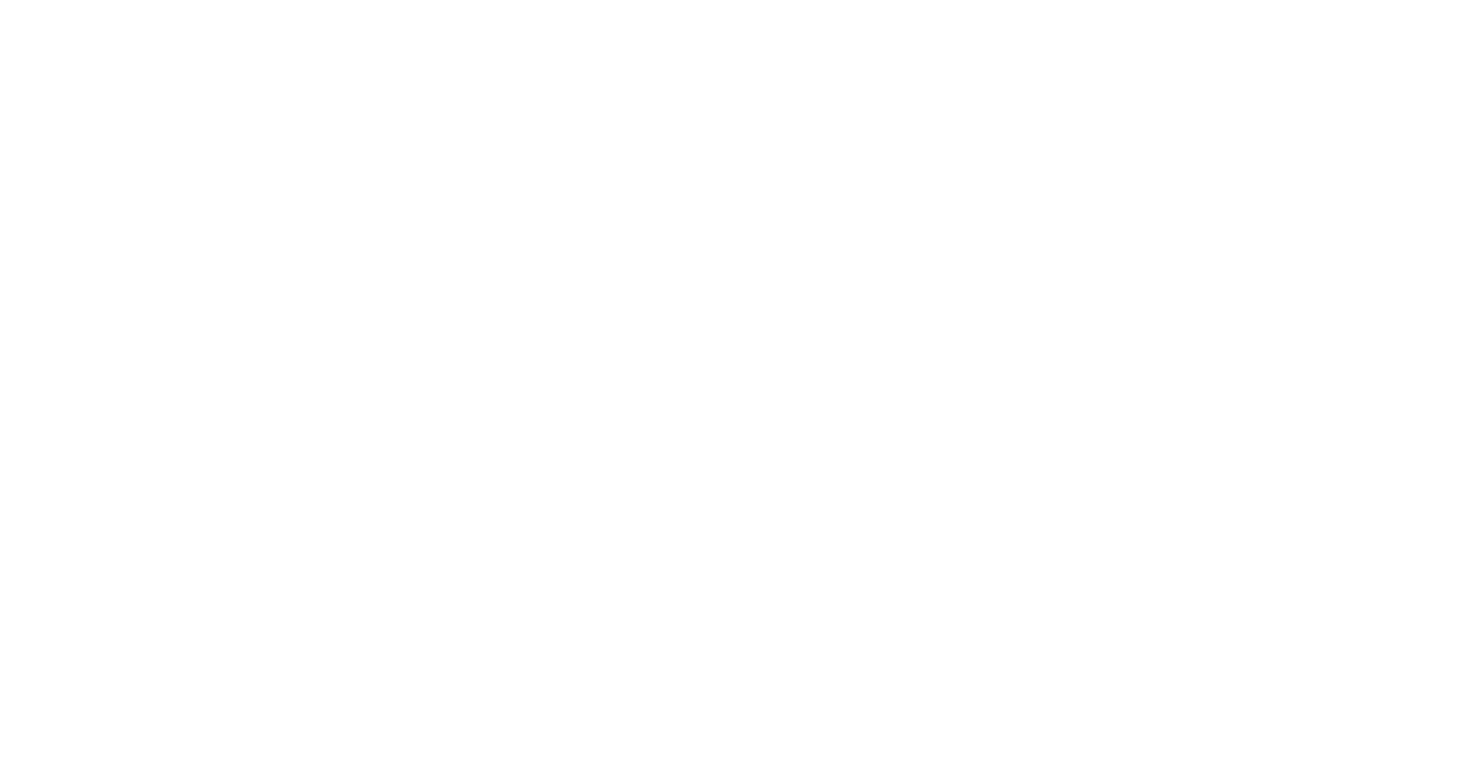Oleh Arya Fernandes
DUKUNGAN mayoritas kader PSI kepada Kaesang Pangarep sebagai ketua umum mungkin merupakan langkah yang paling strategis dan realistis diambil PSI saat ini dibandingkan memilih nama lain.
Meskipun belum berhasil menggerek suara partai hingga 4 persen dalam pemilu lalu, pesona Joko Widodo diyakini masih ampuh untuk membesarkan partai itu. Bahkan Joko Widodo berjanji akan full mendukung dan bekerja keras untuk PSI.
Pilihan strategis untuk memilih Kaesang juga didasarkan pada kebutuhan untuk bertahan dalam kondisi politik yang semakin kompetitif dan semakin terbatasnya pendanaan politik. Kaesang dianggap memiliki daya tarik tersendiri bagi para filantrop politik karena memiliki asosiasi kuat dengan Jokowi. Alasan strategis lainnya adalah figur Jokowi yang masih memikat bagi pemilih terutama di Pulau Jawa.
Dengan memilih Kaesang, PSI ingin sepenuhnya mengasosiasikan diri sebagai “Partai Jokowi” dan sekaligus mempertahankan citra sebagai partai anak muda.
Sikap realistis PSI tersebut membuat Kaesang menang dengan mudah dalam Pemilihan Raya PSI lalu. Kaesang menang dari dua calon lain dengan suara mencapai 65,28 persen.

Di tangan Kaesang yang memimpin partai beberapa bulan menjelang pemilu 2024, sebenarnya terjadi peningkatan suara partai. Perolehan suara partai secara nasional naik dari 1,89 persen pada pemilu 2019 menjadi 2,81 persen pada pemilu 2024. Sementara, di level DPRD provinsi, perolehan kursi partai naik dari 13 menjadi 33 kursi, meskipun masih terkonsentrasi di 4 basis utama yaitu Jakarta (8 kursi), Tanah Papua (8 kursi), NTT (6 kursi), dan Banten (3 kursi).
Fase Politik PSI
Sejarah perjalanan partai menunjukkan kecenderungan meningkatnya pragmatisme politik PSI untuk bisa bertahan. Hal ini sebenarnya terjadi juga pada banyak partai lainnya. Pragmatisme itu tampak dari kebijakan-kebijakan yang berorientasi hasil, manfaat, dan dapat menyesuaikan pilihan-pilihan politiknya untuk mendapatkan keuntungan strategis. Ini tentu tak selalu bermakna negatif.
Saya membagi tiga fase perubahan PSI. Fase pertama (2014-2019) adalah fase idealisme, di mana pendekatan kebijakan politik yang dikedepankan adalah terkait ide dan gagasan besar. Pada fase ini PSI mengampanyekan perang terhadap korupsi, intoleransi, dinasti politik, dan politisi tua. Ini menjadi DNA awal partai. Dalam proses rekrutmen, PSI menolak politisi yang berusia di atas 40 tahun atau sudah pernah berkarier di partai politik sebelumnya.
Fase kedua (2019-2024) adalah fase pragmatis-strategis. Pada fase ini PSI ‘mengoreksi’ semua gagasan ideal di fase pertama. PSI mulai terbuka terhadap dinasti politik, politisi senior serta menerima anggota dari partai lain. Untuk bertahan, PSI mulai mengidentifikasi diri sebagai “Partai Jokowi” dan menunjuk Kaesang sebagai ketua umum partai sehari setelah ia menjadi kader PSI. Dalam fase ini juga sejumlah nama populer memilih hengkang dari PSI seperti: Tsamara Amany, Rian Ernest, Guntur Romli, Surya Tjandra, dan lainnya.
Fase ketiga (2024- ) adalah fase survival PSI. Ini mungkin satu-satunya opsi yang tersisa bagi PSI untuk bisa bertahan dalam politik Indonesia setelah gagal menembus angka ambang batas parlemen 4 persen dalam dua kali pemilu.
Pada fase ini, PSI sepenuhnya menguatkan positioning sebagai partai yang mendukung visi politik Jokowi. Mulai dari mengadopsi gagasan Jokowi tentang “Partai Super Tbk” hingga memilih kembali Kaesang sebagai ketua umum. Pada fase ini PSI mencoba eksperimen baru dengan pelaksanaan pemilihan langsung ketua umum secara e-voting dengan memberikan hak suara pada setiap kader/anggota partai.
Pada Pemilu 2024 lalu, walaupun mendapatkan dukungan dari Jokowi, efek Jokowi belum dapat memberikan dampak besar bagi kenaikan suara partai. Beberapa kemungkinannya adalah sebagai berikut:
Pertama, kemungkinan gagalnya asosiasi PSI dan Jokowi. Hal tersebut tampak dari para loyalis Jokowi yang tidak otomatis memilih PSI. Selain itu bisa juga dipengaruhi karena tidak adanya insentif politik bagi publik untuk mendukung PSI karena program-program pemerintah yang tidak terasosiasi kuat dengan PSI. Hal ini berbeda dengan efek elektoral yang terjadi pada Prabowo Subianto.
Kedua, elite partai yang masih belum berpengalaman dalam kontestasi politik pada banyak daerah pemilihan. Situasi ini diperparah karena absennya mekanisme kompetisi internal di dalam partai. Saat ini seluruh pimpinan partai di daerah ditentukan secara top down oleh pusat, sehingga menghambat munculnya kader-kader potensial di daerah.
Ketiga, infrastruktur partai yang belum disiapkan untuk menghadapi kontestasi politik secara nasional. Dalam dua kali pemilu, tidak terjadi perubahan peta kekuatan di daerah. Daerah-daerah penyumbang suara masih terkonsentrasi di kota-kota metropolitan, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Tangerang Selatan.
Untuk dapat berkembang, perbaikan kelembagaan perlu menjadi catatan serius bagi PSI. Untuk menciptakan iklim kompetisi dan demokratisasi internal, pimpinan partai di daerah sebaiknya dipilih secara langsung oleh kader/anggota seperti halnya Pemilihan Raya, tidak lagi ditunjuk oleh pusat. PSI juga harus memperluas basisnya ke wilayah sub-urban dan rural serta benar-benar melakukan proses kaderisasi politik.
Walaupun mendapatkan dukungan penuh Jokowi, bila tidak ada perbaikan internal yang mendasar seperti kaderisasi, kompetisi internal, dan perluasan infrastruktur partai, PSI masih akan kesulitan untuk menembus 4 persen, apalagi meningkatkan tiga kali lipat suara partai seperti yang diharapkan Jokowi.
Post-incumbency trap akibat ketergantungan PSI pada figur Jokowi perlu dipikirkan secara serius. Dalam jangka pendek, asosiasi dengan Jokowi mungkin masih relevan secara elektoral dan diperlukan. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, PSI akan menghadapi tantangan yang lebih kompleks, sehingga membutuhkan kelembagaan partai yang lebih mapan dan mandiri.